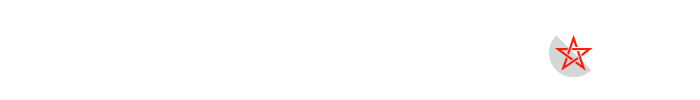Sementara kawasan lain disadari atau tanpa disadari akhirnya hanya mendapat predikat sebagai kawasan kelas dua dan kelas tiga yang hanya memiliki sedikit relevansi dengan Indonesia dari sudut pandang kepentingan politik maupun ekonomi.
Kawasan Pasifik yang berada persis di sebelah kita, misalnya, diperlalukan sebagai rawa-rawa di luar pagar bagian belakang rumah, dan dengan sendirinya dianggap tidak begitu penting. Mungkin hanya ada dua negara di kawasan itu yang dianggap sebagai tetangga. Keduanya adalah Australia dan Selandia Baru. Serta, untuk sedikit relevansi pada hal-hal yang berbau separatisme: Papua Nugini yang berbatasan langsung dengan dua provinsi Indonesia di Papua.
Benua Afrika pun kurang lebih mendapatkan perlakuan begitu. Sampai saat ini anggapan umum yang berkembang di Indonesia masih memandang benua Afrika sebagai benua hitam, benua konflik dan perang saudara tempat darah tumpah begitu saja, benua yang tidak memiliki harapan dan masa depan, dan seterusnya, benua yang hampir-hampir tidak memiliki relevansi sama sekali dengan kepentingan politik dan ekonomi dan dengan sendirinya terabaikan dari wacana pergaulan luar negeri Indonesia. Intinya: benua yang kalau pun tidak ada tidak menjadi masalah bagi kita.
Ketergantungan pada kiblat konvensional ini, belahan utara benua Amerika dan belahan barat Eropa, pada gilirannya melahirkan sikap ketergantungan yang sedemikian rupa pada jalan pikiran dan agenda mereka. Lambat laun Indonesia kehilangan kepercayaan diri dan keberanian dalam menghadapi tekanan lembaga-lembaga internasional ciptaaan kedua belahan bumi itu, seperti World Bank, International Monetary Fund (IMF), World Trade Organization (WTO) dan seterusnya, atau perusahaan-perusahaan multi dan trans nasional mereka yang sesungguhnya telah menjelma menjadi kekuatan kolonial baru di negeri ini. Tekanan dari berbagai lembaga itu kita pandang sebagai kewajiban yang kalau tidak dilaksanakan akan dicatat sebagai dosa.
Ketika berbicara dengan Dutabesar RI untuk Kerajaan Maroko, Tosari Widjaja, penulis merasa senang karena setidaknya ada kesamaan dalam melihat hal tersebut di atas. Tosari adalah mantan anggota Komisi I DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan merupakan salah satu tokoh Nahdlatul Ulama (NU), organisasi massa Islam terbesar di Indonesia dan dunia.
Menurut Tosari, keprihatinan seperti yang sedikit diuraikan di atas sebetulnya sudah ada sejak lama. Namun tidak atau kurang mengemuka dalam narasi besar kebijakan politik luar negeri Indonesia. Mengubah cara pandang seperti itu bukan hal yang mudah, sebut Tosari.
Tosari bertekad memperkuat hubungan Indonesia dengan Maroko yang terletak di utara Afrika baik dalam hal politik maupun ekonomi. Hubungan baik itu sudah ada sejak lama, setidaknya sejak tahun 1950, saat Kerajaan Maroko masih berada di bawah �proteksi� Perancis. Adalah Presiden Sukarno dan Raja Muhammad V yang saling menginspirasi. Setahun sebelum lepas dari proteksi Perancis, Maroko mengirimkan utusan ke Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung yang digagas Presiden Sukarno dengan sejumlah pemimpin negara Asia dan Afrika yang baru merebut kemerdekaan dari kaum kolonial.
Indonesia adalah negara yang penting bagi Maroko. Sementara Sukarno adalah tokoh nasionalis yang sedikit banyak ikut mempengaruhi gerakan nasionalisme Maroko sehingga mereka mendapatkan �kemerdekaan� pada tahun 1956. Untuk memperlihatkan perasaan kagum dan hormat itu, nama Indonesia dan Sukarno diabadikan di Rabat sebagai nama jalan. Bukan hanya Indonesia dan Sukarno, di Rabat juga ada jalan bernama Jakarta dan Bandung. Mangga yang diberikan Sukarno untuk Raja Maroko pun kini masih dikenal masyarakat sebagai Mangga Sukarno. Dan belakangan ini pemerintah Maroko kabarnya mulai mengembangkan kembali upaya budi daya mangga Sukarno itu.
Tetapi hubungan antara Indonesia dan Maroko, demikian Tosari, tidak sekadar menyangkut hal-hal yang bersifat romantisme semata. Hubungan politik dan ekonomi yang lebih baik harus dibangun di atas hubungan sosial dan budaya yang mantap.
Pendidikan salah satunya. Tosari mengapresiasi upaya Maroko sejak beberapa tahun lalu memberikan beasiswa kepada pelajar-pelajar Indonesia dari jenjang pendidikan sarjana sampai doktor. Tosari juga mengajak sejumlah universitas di Indonesia untuk menjalin kerjasama atau sistership dengan sejumlah universitas di Maroko. Universitas Islam Sultan Agung (Unisula) di Semarang, misalnya, barusan menjalin kerjasama dengan tiga universitas Maroko, yakni Universitas Al Ahawain di Ifrane, Universitas Sidi Muhammad bin Abdillah di Fes, dan Universitas Maulay Ismail di Meknes.
Selain itu, Tosari juga memandang Maroko sebagai pintu masuk alternatif ke kawasan penting ekonomi dunia, yakni Eropa, Amerika, Timur Tengah dan Afrika. Maroko memilik perjanjian Free Trade Zone (FTZ) dengan kawasan-kawasan itu. Memperkuat hubungan ekonomi dengan Maroko berarti menciptakan jalan masuk alternatif ke kawasan-kawasan itu.